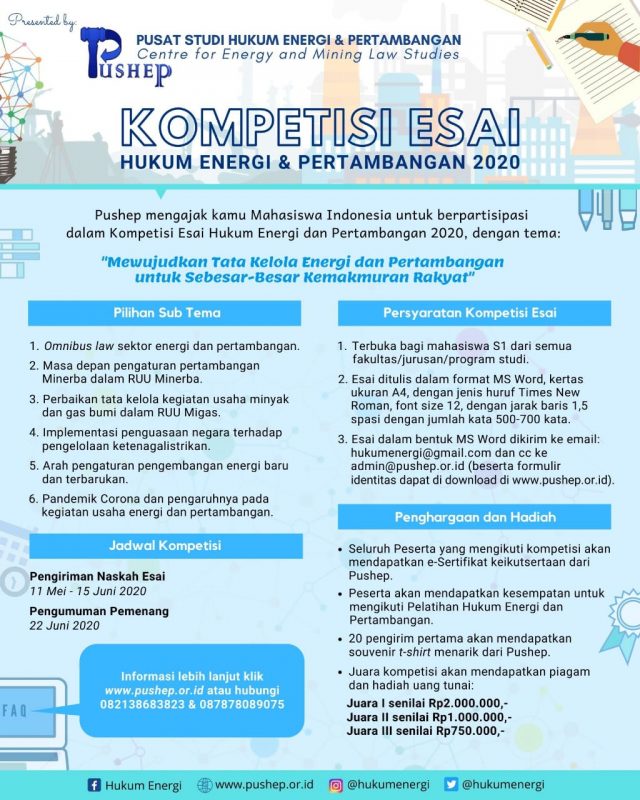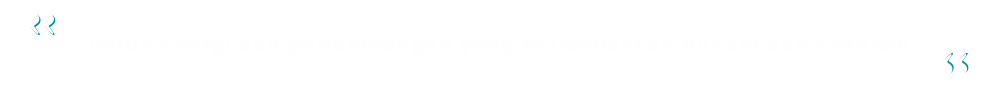Politik Hukum Participating Interest dalam pengelolaan Migas
(Pendekatan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945)
Oleh
M Ilham F Putuhena, SH., M.H.
Peneliti Pusat Hukum Energi dan Pertambangan-PUSHEP
Intisari
Particitipating Interest (PI) daerah sebagai bagian dalam Kontrak Kerja Sama pada Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya. Dengan berbentuk keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dengan mengakomodasi penyertaan BUMD paling banyak 10%.. Banyak daerah yang meminta kepada pemerintah pusat untuk memperoleh hak partisipasi atau participating interest (PI) di blok minyak dan migas (migas) yang berada di wilayahnya. Pemerintah daerah tidak setuju jika hanya diberikan 10% dan meminta hingga lebih. Hal ini disebabkan karena BUMD dari pemerintah daerah yang akan mendapatkan participating interest (PI) akan bekerjasama dengan sawasta. Di satu sisi pemerintah juga berencana melarang adanya kerjasama swasta terhadap BUMD yang akan mengajukan participating interest (PI) daerah. Dari perdebatan pandangan tersebut maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Participating Interest (PI) dengan menggunakan pendekatan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, untuk mengetahui bagaimana arah politik hukum pengaturan Participating Interest dalam pengelolaan Migas dan bagaimana model Participating Interest yang konstitusional dalam pengelolaan Migas yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana data diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Kata Kunci: Politik hukum, Participating Interest
Abstact
Participating Interest (PI) region as part of the Contract of Cooperation on the Management of Oil and Gas Jobs that Will End The cooperation contract. With the form of private sector participation, including public enterprises to accommodate the inclusion of enterprises at most 10%. Many areas are asking the central government to acquire participation rights or participating interest (PI) in the block of oil and gas (oil) situated in its territory, the local government did not even agree if only given 10% and asked to be. This is because enterprises of local governments will get a participating interest (PI) will cooperate with sawasta. On one side of the government also plans to prohibit private cooperation against enterprises that will apply for participating interest (PI) area. From the debate this view, the authors consider it necessary to examine further the Participating Interest (PI) by using the approach of Article 33 of the Constitution NRI 1945, to determine how Directions legal politics setting Participating Interest in the management of oil and gas, and what model Participating Interest are constitutional in the management oil and gas that may encourage the welfare of society. This study uses normative juridical research method, where data were obtained from literature study will be analyzed descriptively qualitative
Key Words: Legal Politics, Participating Interest
A. Pendahuluan
Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu bahwa penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.
Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Terdapat empat faktor yang membuat industri hulu migas berbeda dengan industri lainnya, antara lain: pertama, lamanya waktu antara saat terjadinya pengeluaran (expenditure) dengan pendapatan (revenue). Kedua, keputusan yang dibuat berdasarkan risiko dan ketidakpastian tinggi serta melibatkan teknologi canggih. Ketiga, sektor ini memerlukan investasi biaya kapital yang relatif besar. Keempat, dibalik semua risiko tersebut, industri migas juga menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Risiko tinggi, penggunaan teknologi canggih, dan sumber daya manusia terlatih serta besarnya kapital yang diperlukan, membuat negara, khususnya negara berkembang, merasa perlu mengundang investor asing untuk melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tersebut.[1]
Terkait dengan hal tersebut maka salah satu yang menjadi sorotan dalam pengelolaan Migas saat ini adalah mengenai Particitipating Interest (PI). Baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011. Kedua peraturan a quo menyebutkan bahwa Participating Interest (PI) adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja.
Participating Interest (PI) adalah proporsi kepemilikan produksi dan eksplorasi atas suatu wilayah kerja migas. Participating interest (PI) merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan Participating Interest (PI).
Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, mengatur kesanggupan untuk mengakomodasi kesertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) ditandatangani.[2] Efeknya adalah tak kurang dari tiga belas pemerintah daerah (pemda) yang telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh hak partisipasi atau participating interest (PI) di Blok Minyak dan Gas (Migas) yang berada di wilayahnya. Baik dari Aceh, Madura, Sumatera Selatan, Jambi, Maluku sampai Sumatera Utara. (Sumatera Utara meminta supaya warganya juga dipekerjakan di blok-blok yang ada). Kemudian Kalimantan Timur menjadi pemerintah daerah yang paling banyak meminta besaran participating interest (PI) yakni mencapai 19 persen. Tetapi pemerintah pusat tetap konsisten dan hanya bakal memberikan participating interest (PI) mencapai 10 persen sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, jika ingin 19 persen harus business to business, yaitu pemerintah daerah membeli sendiri saham dari kontraktor yang mengelola Blok Migas tersebut.[3] Dengan itu, BUMD dapat meningkatkan saham partisipasinya melalui farm in atau pengalihan interest dari suatu wilayah kerja yang telah berproduksi, dengan cara business to business.
Daerah penghasil Migas meminta hak partisipasi atau PI pengelolaan migas bisa ditambah menjadi 15-50 persen. Saat ini pemerintah menetapkan daerah hanya akan mendapat jatah participating interest (PI) pengelolaan blok migas yang kontraknya berakhir, sebesar 10%, dan juga menolak rencana pemerintah pusat untuk melarang pemerintah daerah dalam hal ini BUMD bekerjasama dengan pihak swasta.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM), Andang Bachtiar menyatakan tidak setuju dengan jatah participating interest (PI) daerah untuk pengelolaan blok migas perpanjangan, yang hanya 10 persen. Idealnya 15 sampai 50 persen. Dengan pertimbangan wilayah kerja migas yang sudah habis masa kontraknya, memiliki risiko yang lebih rendah. Kontraktor sebelumnya sudah menerima hasil yang lebih banyak saat periode kontrak berjalan. Sehingga wajar pemerintah daerah mendapatkan porsi besar.[4] ADPM juga menolak jika pemerintah daerah dilarang untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam mendapatkan jatah saham blok migas. Kerjasama ini penting bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pendanaan. Apakah PT Pertamina (Persero) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mau menalangi dana yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk mengambil jatah saham tersebut. Apalagi Badan Usaha Milik Daerah yang mewakili pemerintah daerah mendapat PI, portofolio bisnis dan asetnya masih kecil.[5]
Hal senada juga disampaikan Mamit Setiawan, Direktur Executive Energy Watch, berpendapat bahwa pemerintah daerah atau BUMD mempunyai hak participating interest dalam pengelolaan blok migas berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Di satu sisi, participating interest 10% itu merupakan terobosan bagus untuk meningkatkan kemandirian BUMD, sehingga tidak menjadi tunggangan pemodal melalui pengelolaan participating interest. Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa tidak diperbolehkannya swasta untuk terlibat harus dikaji lagi, mengingat tidak semua BUMD mempunyai modal yang cukup untuk bisa terlibat dalam participating interest 10%. Selain itu, jika BUMD yang menjalankan sepenuhnya participating interest 10%, apakah BUMD memiliki tenaga ahli yang memadai dan kompeten sesuai kualifikasi teknis yang dibutuhkan?[6]
Karena industri perminyakan merupakan industri padat modal serta berisiko tinggi, untuk membagi risiko dan beban biaya tersebut, maka perlu keterlibatan swasta bersama BUMD dalam pengelolaan participating interest 10% tersebut. Berbeda jika swasta dilibatkan dalam participating interest 10%, maka swasta bisa bekerja secara profesional dengan modal yang dimiliki, swasta bisa membantu pemberdayaan BUMD daerah, transfer keahlian, dan berkembangnya iklim investasi di daerah. Manfaat ganda dari keterlibatan swasta dalam participating interest 10% bagi pemda adalah selain menerima pendapatan dari kerja sama dengan swasta. Pemda juga bisa menerima pendapatan dana bagi hasil migas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dengan melibatkan swasta dalam participating interest pengelolaan blok minyak dan gas bumi BUMD akan mendapatkan keuntungan penuh sementara resiko akan ditanggung pihak swasta. Seharusnya fungsi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak lebih adalah sebagai pihak yang mengawasi partisipasi swasta dalam hak participating interest 10% tersebut, dengan sebelumnya pihak swasta telah melalui uji kelayakan dan proses review dari pemda setempat dan Kementerian ESDM.
Pasal 33 PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat mengalihkan, menyerahkan dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (participating interest) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM. Di mana pengalihan, penyerahan dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban KKKS tersebut kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama. Menteri ESDM dapat meminta KKKS untuk menawarkan lebih dulu kepada perusahaan nasional.
Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja, Pemerintah menegaskan kembali, besaran hak partisipasi atau Participating Interest (PI) untuk daerah penghasil migas tidak mengalami perubahan atau tetap 10%. Apabila besaran saham untuk daerah ditambah dengan cara priviledge, dikhawatirkan membuat investor tidak tertarik lagi berinvestasi migas di Indonesia. Jadi kita harus balance, BUMD dapat dan investor juga dapat.[7]
Khusus untuk Aceh, pemerintah pusat sendiri berjanji akan memberikan hak keistimewaan terkait pembagian PI Blok Migas. Ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Aceh, yang menjadi turunan dari perjanjian damai dan refleksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh mendapat 25 persen karena ada aturan dan ketentuannya. Sedangkan pemda yang lain maksimal 10 persen.[8]
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membuat aturan mengenai hak partisipasi daerah di blok migas. Dalam aturan yang akan segera keluar ini, daerah akan diwakili oleh BUMD yang 100 persen dimiliki oleh pemerintah daerahnya. Untuk masalah pendanaan, kementerian menyiapkan tiga alternatif yang bisa dilakukan pemda jika tidak mampu secara finansial. Pemda bisa meminjam dana melalui PIP. Alternatif pembiayaan lainnya adalah bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) atau kontraktor yang mengelola blok tersebut dengan cara kontraktor membiayai terlebih dahulu, nanti Pemda membayarnya pada saat produksi. Sehingga keuntungan daerah lebih besar.[9]
Menurut Faisal Basri terkait hak partisipasi daerah untuk mengelola blok migas ini, menentang campur tangan swasta yang bekerjasama dengan daerah. Hak partisipasi daerah harus sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh daerah tersebut. BUMD di daerah tidak boleh ada swasta. Namun, BUMD juga tidak boleh dibebani dengan pengeluaran biaya investasi dan risiko kerugian negara.[10]
Dari perdebatan pandangan tersebut di atas maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Participating Interest (PI) dengan menggunakan pendekatan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi akan pengaturan Participating Interest yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.
B. Permasalahan
Sebagaimana dari pembahasan tersebut di atas maka, terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji, yaitu:
- Bagaimana arah politik hukum pengaturan participating interest dalam pengelolaan migas?
- Bagaimana model participating interest yang konstitusional dalam pengelolaan migas yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat?
C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.[11] Data diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
D. Pembahasan
1. Konsep Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Pembahasan ini akan dimulai dari melihat bagaimana konsep hubungan pemerintah dan swasta. Hal ini terkait bahwa saat ini BUMD yang merupakan milik pemerintah daerah dalam pelaksanaan PI bekerjasama dengan swasta. Sehingga, dipandang perlu untuk membahas sekilas mengenai konsep tentang kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnerships (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerja sama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Di mana kerja sama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik.[12] Public-Private Partnerships (PPP) adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi di antara sektor publik (pemerintah) dan pihak swasta dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pelayanan lain. Public-Private Partnerships (PPP) merupakan bentuk kerjasama antara pelaku pembangunan untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan melalui pencapaian investasi. Pelaku Public-Private Partnerships (PPP) terdiri dari pemerintah, masyarakat, investor/pengusaha dan Non Government Organization (NGO). Para pelaku tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda dalam melakukan pembangunan.[13]
Pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama pemerintah dengan swasta yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi sebagai berikut:[14]
1. Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong perwujudan good governance and good society
2. Alasan administratif: adanya keterbatasan sumber daya pemerintah, baik sumber daya anggaran, sumber daya manusia, aset, maupun kemampuan manajemen.
3. Alasan ekonomis: mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas, serta mengurangi resiko.
Menurut Parente dari USAID Environmental Services Program Public-Private Partnerships (PPP) adalah “An agreement or contract, between a public entity and a private party, under which: (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party.” Dalam kutipan tersebut dinyatakan, bahwa Public-Private Partneships (PPP) merupakan suatu perjanjian kerja sama atau kontrak, antara instansi pemerintah dengan badan usaha/pihak swasta; (a) pihak swasta melaksanakan sebagian dari fungsi pemerintah selama waktu tertentu. (b) pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. (c) pihak swasta bertanggungjawab atas risiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut, dan (d) fasilitas pemerintah, lahan atau aset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta selama masa kontrak.[15]
Melalui perjanjian kontrak kerjasama ini, aset-aset dan keahlian kedua belah pihak disumbangkan untuk melayani kepentingan umum dan fasilitas-fasilitas pihak membagi risiko dan keuntungan pada setiap sektor yang dikerjasamakan. Pihak swasta memainkan peran memperbaiki (to renovate), membangun (to construct), mengoperasikan (to operate), memelihara (to maintain) dan/atau mengelola sebagian atau seluruh fasilitas atau sistem yang menyediakan pelayanan umum. Tujuan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur adalah efisiensi pelayanan fasilitas umum. Untuk meyakinkan masyarakat, maka ada fungsi monitoring atau pengawasan terhadap ketetapan-ketetapan perjanjian/kontrak kerjasama dan pengoperasiannya. Dengan demikian, harapannya adalah bahwa semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat mendapat keuntungan (manfaat).[16]
Bentuk-bentuk kerjasama PPP dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
- Kepemilikan aset. Kepemilikan aset merupakan hak atas kepemilikan terhadap aset yang dikerjasamakan, apakah aset itu berada di tangan pemerintah atau swasta, selama jangka waktu tertentu. Semakin besar keterlibatan pihak swasta dalam kepemilikan aset maka akan semakin menarik minat mereka bekerjasama/berinvestasi. Kepemilikan aset dapat dibedakan apakah menjadi milik pemerintah, milik swasta, atau milik pemerintah dan swasta (kepemilikan bersama).
- Operasional dan pengelolaan aset. Operasional dan pengelolaan aset merupakan kriteria yang mengindentifikasikan pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola aset yang dikerjasamakan selama kurun waktu tertentu. Pihak yang mengelola berpeluang untuk memperoleh pendapatan dari aset kerjasama. Operasional dan kepemilikan aset dapat dibedakan menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta, atau tanggung jawab bersama.
- Investasi modal atau penanam modal. Investasi modal merupakan kriteria berkaitan dengan siapa yang akan menanamkan modal tersebut pada aset yang akan dikerjasamakan. Investasi modal dapat dibedakan menjadi investasi pemerintah, swasta, atau investasi dengan modal bersama.
- Risiko-risiko yang akan terjadi. Risiko komersial merupakan kriteria yang berhubungan siapa yang akan dibebani dengan risiko-risiko komersial tersebut yang nanti akan muncul selama pembangunan dan pengelolaan aset yang dikerjasamakan. Risiko komersial yang akan terjadi dapat dibebankan kepada pemerintah, swasta, atau menjadi beban bersama.
- Durasi kerjasama. Durasi kerjasama merupakan kriteria yang berkaitan dengan jangka waktu kerjasama yang disepakati. Semakin lama jangka waktu kerjasama akan memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembalian. Durasi kerjasama dapat dibedakan menjadi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
Jika dikaitkan dengan Prticipating Interest yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan bentuk BUMD, pada dasarnya perlu melihat bagaimanakah konsep pengelolaan migas di Indonesia dan dimanakah posisi pemerintah daerah dalam proses tersebut khususnya dikaitkan dengan mekanisme Prticipating Interest. Untuk itu selanjutnya perlu dikaji mengenai mengenai konsep pemerintah daerah dan BUMD itu sendiri.
2. Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
Secara normatif pemerintah daerah diatur dalam pasal 1 huruf angka 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah didasarkan dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Di samping itu, melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.
Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal. Sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah (perda) maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Dana dalam hal ini mengenai pengelolaan Migas yang menjadi kepentingan Nasional.
Jika dikaitkan dengan peran BUMD dalam Participating interest maka perlu juga kita pahami bahwa BUMD sebagai perusahaan milik daerah merupakan salah satu sarana pemerintah daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).[17] Saat ini pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efesien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatiaan serius adalah pengelolaan PAD karena harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah.
PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari BUMD. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tentang BUMD. Pasal 331 ayat (3) menyatakan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum daerah[18] dan perusahaan perseroan daerah[19]. Ayat (4) Pendirian BUMD bertujuan untuk a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Sehingga BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.[20]
Tetapi keberadaan BUMD juga bukan tanpa permasalahan kemampuan BUMD dalam melaksanakan fungsinya secara optimal dalam melaksanakan pelayanan sosial dan ekonomi atas dasar prinsip bisnis masih menjadi msalah. Keberadaan BUMD memiliki banyak benturan yang dihadapi misalnya tidak efisien, modalnya dari pemerintah, selalu merugi tidak menyumbang PAD, kualitas SDM yang rendah dan tidak profesional, lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran yang sulit bersaing, kurangnya perhatian dan pemeliharaan aset yang dimiliki sehingga rendahnya produktivitas, serta mutu dan ketepatan hasil produksi. Dengan realitas seperti itu maka bagaimanakah sebenarnya konsep pengelolaan migas yang konstitusional dan bagaimana hubungan pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan migas tersebut.
3. Konstitusionalitas Pengelolaan Hulu Migas
Kegiatan usaha hulu Migas adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
Kegiatan hulu migas (eksplorasi dan eksploitasi) merupakan kegiatan investasi berdimensi jangka panjang (10 sampai dengan 30 tahun), mengandung risiko finansial, teknikal, operasional yang besar, menuntut profesionalisme dan sumber daya manusia yang handal, serta modal yang besar. Mitra investor migas adalah lintas yurisdiksi negara. Industri hulu secara alami akan menyaring para pelaku bisnis yang dapat menggelutinya. Untuk itu mutlak diperlukan kehadiran negara melalui kebijakannya untuk mengatur sehingga ada keseimbangan antara tujuan komersial, keberlanjutan penyediaan cadangan pengganti, kontribusi makro ke perekonomian nasional, dan penguatan kapasitas nasional untuk berpartisipasi.[21]
Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 yang merujuk putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenai pengujian UU Migas. Mahkamah Konstitusi telah memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Bahwa secara konsepsi penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Putusan tersebut mempertimbangkan bahwa makna “dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan hanya sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam Undang-Undang Dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD NRI 1945, kewenangan negara untuk mengatur tetap ada pada negara, bahkan dalam negara yang menganut paham ekonomi liberal sekalipun. Oleh karena itu, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mempertegas pengertian “penguasaan negara” dimaknai rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan:
- Kebijakan (beleid);
- Tindakan pengurusan (bestuursdaad), Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie)
- Pengaturan (regelendaad), Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah;
- Pengelolaan (beheersdaad), Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.
Dan terkait dengan hubungan antara pemerintah dengan pihak swasta terlihat dari bagaimana keberadaan BP Migas yang kemudian dianggap inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Kontitusi, model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Walaupun UU Migas, menentukan tiga syarat minimal dalam KKS, yakni i) kepemilikan sumber daya alam di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan, ii) pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan iii) modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi ketiga syarat minimal tersebut tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan dengan efektif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Implikasi dari model hubungan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi terdapat tiga hal yang terjadi, yaitu: pertama, pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu. Kedua, setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS, yang berarti negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS. Ketiga, tidak maksimalnya keuntungan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan migas untuk keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan.
Dengan konstruksi penguasaan migas melalui BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola sumber daya alam Migas. Padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena konstruksi hubungan yang demikian maka menurut Mahkamah, keberadaan BP Migas bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam migas yang membawa kuntungan lebih besar bagi rakyat.
Menurut Mahkamah Konstitusi, pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Hanya dalam batas-batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam migas, maka pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta. Bahwa untuk mengembalikan posisi negara dalam hubungannya dengan sumber daya alam Migas, negara/pemerintah tidak dapat dibatasi tugas dan kewenangannya pada fungsi pengendalian dan pengawasan semata tetapi juga mempunyai fungsi pengelolaan.
Pemisahan antara badan yang melakukan fungsi regulasi dan pembuatan kebijakan dengan lembaga yang melakukan pengelolaan dan bisnis migas secara langsung, menurut Mahkamah Konstitusi telah mengakibatkan terdegradasinya penguasaan negara atas sumber daya alam migas. Walaupun terdapat prioritas pengelolaan migas diserahkan kepada BUMN sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004. Efektivitas penguasaan negara justru menjadi nyata apabila pemerintah secara langsung memegang fungsi regulasi dan kebijakan (policy) tanpa ditambahi dengan birokrasi dengan pembentukan BP Migas.
Dalam posisi demikian, pemerintah memiliki keleluasaan membuat regulasi, kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya alam Migas. Dalam menjalankan penguasan negara atas sumber daya alam Migas, pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas sumber daya alam Migas dengan memberikan konsesi kepada satu atau beberapa BUMN untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor hulu. BUMN itulah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau Bentuk Usaha Tetap. Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan negara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata.
Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa pola hubungan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Migas tidak dapat dilakukan sama seperti dengan hubungan pemerintah dan swasta disektor lain seperti infrastruktur pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga jika konsisten dengan cara pandang Mahkamah Konstitusi tersebut maka beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam participating interest adalah:
- participating interest merupaka mekanisme yang dibuat untuk mengakomodir aspirasi daerah dan untuk melindungi kepentingan masyarakat di daerah agar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bukan untuk kepentingan swasta, apa lagi swasta yang tidak berasal dari daerah lokasi Migas tersebut.
- bahwa pelaksanaan participating interest harus melibatkan BUMD yang merupakan perusahaan umum daerah, sehingga modal BUMD tersebut merupakan modal Pemerintah daerah itu sendiri atau gabungan dari pemerintah daerah.
- dengan kepemilikan BUMD yang murni dibiayai oleh pemerintah daerah maka keuntungan dari participating interest akan didapatkan secara maksimal oleh daerah atau beberapa daerah. Dengan adanya perusahaan swasta dalam BUMD tersebut maka keuntungan kepada daerah akan berkurang
- kepemilikan BUMD yang murni dibiayai oleh pemerintah daerah maka keuntungan dari participating interest juga memberikan akses yang besar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan Migas dengan KKKS, tanpa harus dikaitkan denga kepentingan pemodal swasta apabila terjadi permasalahan, sehingga pemerintah daerah tidak terganggu atau tergantung dengan pengaruh swasta.
- dengan adanya kebijakan participating interest memberikan konsekwensi untuk pemerintah pusat harus melakukan dua hal yaitu menyiapkan supporting sarana permodalan bagi daerah, dan sekaligus mengarahkan serta mebina daerah untuk dapat memanfaatkan participating interest secara tepat.
E. Penutup
1. Kesimpulan
Dari pembahsan yang dilakukan maka kesimpulannya adalah:
- pola hubungan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Migas tidak dapat dilakukan sama seperti dengan hubungan Pemerintah dan swasta di sektor lain seperti infrastruktur pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga harus konsisten dengan cara pandang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemerintah harus memiliki keleluasaan membuat regulasi, kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya alam Migas. Dalam menjalankan penguasan negara atas sumber daya alam Migas, Pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas sumber daya alam Migas dengan memberikan konsesi kepada satu atau beberapa BUMN untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor hulu. BUMN itulah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau Bentuk Usaha Tetap. Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan negara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata. Sehingga apabila swasta juga terlibat dalam BUMD maka Pemerintah dalam hal ini Pemda tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan dalam BUMD. Pemda kehilangan kebebasannya untuk melakukan kebijakan yang bertentangan dengan kerjasama dengan swasta; Ketiga, tidak maksimalnya keuntungan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan keuntungan dari participating interest oleh swasta atau mengurangi keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat didaerah melaluai BUMD.
- Participating Interest merupakan mekanisme yang dibuat untuk mengakomodir aspirasi daerah dan untuk melindungi kepentingan masyarakat di daerah agar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bukan untuk kepentingan swasta apa lagi swasta yang tidak berasal dari daerah lokasi Migas tersebut. Sehingga kebijakan participating interest juga harus di dukung dengan kebijakan lain berupa menyiapkan supporting sarana permodalan bagi daerah dan sekaligus mengarahkan serta membina daerah untuk dapat memanfaatkan participating interest secara tepat.
2. Saran
Dari kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah pembrian participating interest sebaiknya hanya diberikan kepada BUMD yang sepenuhnya milik pemerintah daerah atau beberpa pemerintah daerah. Kemudian pemerintah harus segera menyiapkan bantuan permodalan bagi daerah untuk menunjang kebijakan tersebut, seperti keterlibatan BUMD sektor perbankan.
Daftar Pustaka
Buku
Benny Lubiantara, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak
Migas, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indoneia, 2002.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika
Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad
Ke-20, Alumni, Bandung, 1994.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
IR. Purwadi, Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non
Perbankan dalam MeningkatkanPendapatan Asli Daerah. (Surabaya : Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002), hlm. 3.
Sampe L. Purba, Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam
Revisi UndangUndang, makalah dalam diskusi publik di Hotel Grand Sahid Jaya, 4 Desember 2013.
Tri Widodo Utomo. “Pengembangan Kerjasama Pemerintah Dengan
Masyarakat Dan Swasta Dalam Pembangunan Daerah”, Makalah. Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2004
Djunaedi, Parptono. 2007. Implementasi Public-Private Partnerships
dan Dampaknya ke APBN. Majalah Warta Anggaran edisi 6. Jakarta: Direktorat Jendral Anggaran.
Artikel
Ahita Nur Aisyah Zen dan Nurkholis, Ph.D., Ak., CA., artikel Analisis
Participating Interest (PI) Dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Pemerintah Daerah Dan Swasta (Studi Kasus pada Sektor Migas Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro), Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang,
Peraturan
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya
Putusan Pengadilan
Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 002/PUU-I/2003 pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Internet
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150703194240-85-
64247/setidaknya-13-daerah-minta-saham-di-blok-migas/
http://katadata.co.id/berita/2015/05/21/daerah-minta-jatah-sahamnya-di-
blok-migas-ditambah-jadi-50 persen#sthash.T8SESGj7.MGKlKXur.dpuf
http://industri.bisnis.com/read/20150409/44/421098/hak-participating-
interest-10-larangan-keterlibatan-swasta-perlu-dikaji-ulang
http://www.migas.esdm.go.id/post/read/participating-interest-daerah-tetap-
10-persen
http://katadata.co.id/berita/2015/05/21/daerah-minta-jatah-sahamnya-di
blok-migas-ditambah-jadi-50-persen#sthash.T8SESGj7.MGKlKXur.dpuf
http://www.ncppp.org/about/overview-mission/
http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/974.
[1] Benny Lubiantara, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indoneia, 2002, hal. 5
[2] Lihat pengaturan mengenai PI dalam Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2015 diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 4 ayat 3 poin h apabila permohonan pengelolaan dilanjutkan oleh pertamina, kemudian Pasal 8 huruf a ke 8, apabila permohonan pengelolaan dilanjutkan oleh kontraktor, serta Pasal 11 huruf c dan pasal 16 huruf b dalam hal permohonan perpanjangn diajukan PT Pertamina dengan Kontraktor Swasta, kemudian pasal 16, huruf b, pasal 20 huruf b dan c, pasal 22 huruf b dan c, pasal 23.
[3] Lihat http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150703194240-85-64247/setidaknya-13-daerah-minta-saham-di-blok-migas/
[4]Lihat http://katadata.co.id/berita/2015/05/21/daerah-minta-jatah-sahamnya-di-blok-migas-ditambah-jadi-50-persen#sthash.T8SESGj7.MGKlKXur.dpuf
[5] Ibid.
[6] Lihat:http://industri.bisnis.com/read/20150409/44/421098/hak-participating-interest-10-larangan-keterlibatan-swasta-perlu-dikaji-ulang
[7] http://www.migas.esdm.go.id/post/read/participating-interest-daerah-tetap-10-persen
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10]Ibid.http://katadata.co.id/berita/2015/05/21/daerah-minta-jatah-sahamnya-di-blok-migas-ditambah-jadi-50-persen#sthash.T8SESGj7.MGKlKXur.dpuf
[11] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan ( Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.); Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hal. 147); Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hal. 139); dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 10).
[12] The National Council for Public-Private Partnership (NCPPP) mendefinisikan public-private partnership (P3) sebagai perjanjian kontrak (kerjasama) antara agen-agen publik (negara, negara bagian, daerah) dan sektor sektor swasta, Lihat http://www.ncppp.org/about/overview-mission/
[13] Ahita Nur Aisyah Zen dan Nurkholis, Ph.D., Ak., CA., artikel Analisis Participating Interest (PI) Dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Pemerintah Daerah Dan Swasta (Studi Kasus pada Sektor Migas Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro), Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/974.
[14] Tri Widodo Utomo. “Pengembangan Kerjasama Pemerintah Dengan Masyarakat Dan Swasta Dalam Pembangunan Daerah”, Makalah. Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2004
[15] Ibid Ahita Nur Aisyah Zen dan Nurkholis, hal 4, mengutip dari Djunaedi, Parptono. 2007. Implementasi Public-Private Partnerships dan Dampaknya ke APBN. Majalah Warta Anggaran edisi 6. Jakarta: Direktorat Jendral Anggaran. Hlm 1.
[16] Lihat http://www.ncppp.org/about/overview-mission/
[17] Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), kemudian dalam Pasal 40 ayat (1) UU no 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari: a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN; b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah Persiapan; c. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[18] Dalam UU 23 tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 334 ayat (1) bahwa Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
[19] Dalam UU 23 tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 339 ayat (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Ayat (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
[20] IR. Purwadi, Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam MeningkatkanPendapatan Asli Daerah. (Surabaya : Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002), hlm. 3.
[21] Sampe L. Purba, Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi UndangUndang, makalah dalam diskusi publik di Hotel Grand Sahid Jaya, 4 Desember 2013.
Sumber: tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Selesik, Volume 2, Nomor 2, Januari 2016