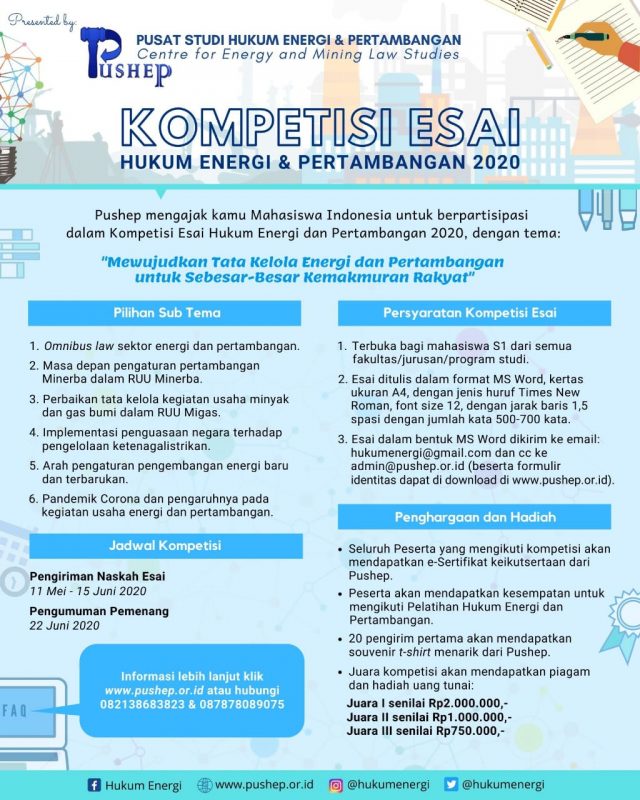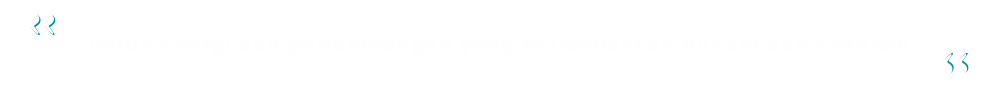Pengaturan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut tentu memiliki konsekuensi tersendiri terhadap berbagai ketentuan yang akan telah ada sebelumnya. Begitupun dengan pengaturan mengenai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hingga saat ini belum memiliki kejelasan atau cantolan hukum yang tepat. Menyikapi hal tersebut Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) melakukan kajian terhadap permasalahan ini. Dalam kajian tersebut, Ilham Putuhena sebagai pembicara menyampaikan mengenai sejarah pengaturan pertambangan minerba dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).
Menurut Ilham Putuhena, sejarah awal penemuan tambang batu bara di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1846 di Pengaran, Kalimantan Timur, yang sudah sampai pada tahap dilakukan eksplorasi, Di tahun 1880, juga ditemukan di Sungai Durian, Sumatera Barat. Penemuan tambang batubara selanjutnya terjadi di tahun 1888, di Pelarang Samarinda, Kalimantan Timur. Penemuan berikutnya dalam catatan sejarah terjadi pada tahun 1919 di Tanjung Enim – Bukit Asam, Sumatera Selatan.
Sejarah pengaturan pertambangan mineral dan batubara dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase pada saat Zaman Kolonial, fase Orde Lama, fase Orde Baru dan fase Reformasi. Zaman kolonial sudah terdapat aturan yang nantinya akan digunakan sebagai landasan hukum melakukan pertambangan dan batu bara yaitu Indische Mijn Wet 1899. Dalam IMW tersebut pada pasal 5 dan 5A menyebutkan bahwa terdapat dua hubungan dalam melakukan kegiatan usaha tambang dan batu bara, yaitu konsesi dan kontrak.
Selanjutnya, pada masa Orde Lama, dasar hukum pertambangan menggunakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1) UUDS 1950, Surat DPR RI No.Agd.1446/RM/DPRRI/ 1951, UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (mengatur hubungan antara negara dengan swasta, semangat nasionalis dijunjung tinggi oleh Negara), UU No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan, UU No. 37 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan. Berikutnya di masa Orde Baru, dasar hukum yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPRS No. XXIII – MPRS/1966, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Akhirnya pada masa orde baru UU PMA dan Pokok-Pokok Pertambangan mengalami perubahan dengan menyesuaikan kepentingan umum.
Saat masa reformasi, ketentuan terkait pertambangan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK No.01-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan MK lainnya, Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU Otoda) dan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun ketentuan dalam Putusan MK merumuskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh BUMN. Selanjutnya terdapat aturan-aturan baru yang menyesuaikan kebutuhan, seperti UU PMA yang mengakomodir kepentingan negara dan tetap menarik bagi para investor. Selain itu, keberadaan UU Otoda mempunyai pengaruh yang besar (memberikan batasan terkait urusan rumah tangga daerah dan urusan rumah tangga pusat) membuat daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pertambangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, terdapat penyesuaian-penyesuaian pokok yang menjadi kekuatan bagi pengaturan model bisnis pertambangan batubara, yaitu ketentuan mengenai model perizinan. Dalam undang-undang sebelumnya model bisnis yang diterapkan masih menggunakan rezim kontrak. Sementara UU 4 Tahun 2009 menggunakn rezim izin usaha.
Konstitusionalitas pengaturan KK dan PKP2B harus dilihat dari tafsiran Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, sepanjang frasa “dikuasai oleh negara” dalam Putusan MK No.01-021-022/PUU-I/2003. Dalam putusan a quo dikatakan bahwa bentuk penguasaan negara harus dimaknai sebagai kesatuan fungsi, berupa fungsi kebijakan (beleid), fungsi pengurusan (bestuursdaad) yang mencakup perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie), fungsi pengaturan (reglendaad), dimaknai sebagai kewenangan legislasi dan regulasi, fungsi pengelolaan (beheersdaad), yang mencakup pemilikan saham (share-holding), dan/atau sebagai instrumen kelembagaan dan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad), berupa mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penguasaan oleh negara.
Dampak dari putusan itu adalah menghapus konsep kontrak dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, ketentuan KK dan PKP2B dalam UU No. 4 Tahun 2009 diatur dalam ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa KK dan PKP2B tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Selanjutnya dikatakan penyesuaian perjanjian KK dan PKP2B selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang diberlakukan kecuali mengenai penerimaan negara. Pengecualian itu adalah upaya peningkatan penerimaan negara.
Perpanjangan KK dan PKP2B selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksana yaitu di peraturan pemerintah (PP No.23 Tahun 2010). Menurut Ilham Putuhena, perpanjangan KK dan PKP2B diatur dalam peraturan pelaksana lainnya, bukan lagi dalam undang-undang. Perpanjangan itu sendiri selalu ditemukan dalam peraturan pemerintah, yang sebenarnya tidak pernah didelegasikan oleh UU Minerba. Sampai saat ini peraturan pemerintah telah mengalami 5 kali perubahan.
Adapun upaya pengaturan mengenai perpanjangan KK dan PKP2B saat ini diatur dalam Permen ESDM No 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberia Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Ilham Putuhena, ketentuan tersebut tidak tepat mengingat kegiatan usaha pertambangan merupakan industri yang menguasai hajat orang banyak dan oleh karenanya pengaturan akan hal tersebut harus didasarkan pada ketentuan undang-undang.